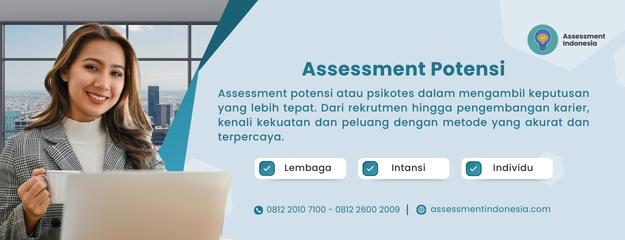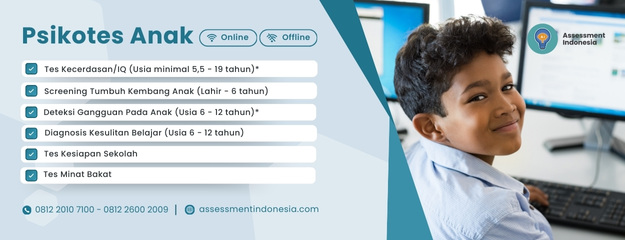Belum lama ini, masyarakat Indonesia di berbagai daerah turun ke jalan untuk menyuarakan pendapatnya melalui demonstrasi. Namun, apa yang awalnya dirancang sebagai gerakan terarah dengan tujuan yang jelas, pada akhirnya berubah menjadi peristiwa yang penuh kekacauan dan kekerasan. Situasi seperti ini tidak hanya meninggalkan dampak fisik atau sosial, tetapi juga dapat menorehkan luka psikologis yang dirasakan bersama. Fenomena inilah yang dikenal dengan istilah collective trauma.
Collective Trauma
Collective trauma, atau trauma kolektif menurut APA (2024), adalah trauma kolektif adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang tidak hanya berdampak pada satu individu, tetapi juga menyayat psikologis sekelompok orang yang memiliki identitas atau keterikatan bersama. Ini mencakup interaksi traumatis antar kelompok dan sistem yang merugikan masyarakat. Trauma kolektif yang disebabkan oleh kelompok bisa terjadi antara kelompok minoritas dan mayoritas, seperti kekerasan berbasis gender, penghinaan mikro (micro-aggression), hingga kejahatan kebencian (macro-aggression). Di sisi lain, trauma yang disebabkan oleh sistem bisa disebabkan oleh pemerintahan atau non-pemerintahan yang melanggengkan diskriminasi, perang, penganiayaan politik dan agama, perdagangan manusia, dan penyiksaan.
Community-Based Social Healing
Trauma kolektif tidak hanya meninggalkan luka pada individu, tetapi juga merusak ikatan sosial yang ada di dalam masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, trauma kolektif muncul dari peristiwa besar yang berdampak pada banyak orang sekaligus, mulai dari konflik sosial, bencana, diskriminasi sistematis, hingga kekerasan politik. Dalam konteks ini, proses pemulihan tidak cukup dilakukan hanya di tingkat individu, melainkan juga harus melibatkan dimensi sosial yang lebih luas. Di sinilah konsep community-based social healing menjadi penting.
Prinsip dasar dari community-based social healing (Fanahei, 2024) adalah pengakuan terhadap “kekuatan” komunitas. Masyarakat memiliki potensi untuk saling menguatkan, membangun solidaritas, serta menciptakan ruang aman bagi anggotanya untuk pulih bersama. Namun, jika setiap komunitas selalu mampu memanfaatkan kekuatannya secara penuh, maka intervensi eksternal tidak akan diperlukan. Faktanya, dalam banyak kondisi krisis, komunitas juga mengalami keretakan dan kehilangan arah. Karena itu, dibutuhkan upaya untuk menata kembali atau bahkan membentuk ulang komunitas tersebut agar dapat kembali berfungsi sebagai wadah yang menyembuhkan.
Konsep penyembuhan komunitas (community healing) memiliki dua dimensi utama. Pertama, bekerja dengan komunitas yang sudah ada, namun perlu diarahkan atau diperkuat kembali. Kedua, membentuk komunitas baru dari kelompok-kelompok yang sebelumnya tercerai-berai. Dalam kedua dimensi ini, tujuan utamanya bukan sekadar membentuk komunitas baru, melainkan menciptakan rasa kebersamaan yang bermakna, di mana individu merasa diakui, diterima, dan didukung.
Trauma memang selalu dialami secara personal setiap individu merasakannya dengan cara yang unik. Namun, individu-individu ini juga merupakan bagian dari formasi sosial yang lebih besar, baik itu komunitas lokal, kelompok berdasarkan identitas tertentu, atau bahkan kategori abstrak seperti “korban konflik” atau “penyintas bencana”. Misalnya, ketika terjadi gempa bumi di Lombok atau Cianjur, banyak orang terpaksa mengungsi dan kehilangan rumah serta jaringan sosial mereka. Secara abstrak, mereka adalah “penyintas bencana”. Namun, bagaimana caranya membantu kategori abstrak seperti itu? Jawabannya adalah dengan membangun komunitas konkret di tempat pengungsian berupa komunitas kecil. Komunitas tersebut dibentuk berdasarkan faktor nyata seperti lokasi, kebutuhan sehari-hari, dan pengalaman bersama. Melalui komunitas inilah dukungan dapat diberikan secara lebih nyata, dan para penyintas tidak lagi merasa sendiri dalam menghadapi trauma.
Healing Leader
Dalam proses ini, peran kepemimpinan menjadi penting. Sebuah komunitas, bahkan yang paling kompak sekalipun, biasanya membutuhkan arah. Di sinilah muncul konsep “healing leader”, seseorang atau sekelompok orang yang berperan sebagai agen perubahan. Tugas mereka bukan sekadar memimpin secara administratif, melainkan menciptakan, memelihara, dan mengarahkan komunitas ke arah yang lebih sehat. Healing leader bisa berasal dari anggota komunitas sendiri atau merupakan intervensi eksternal sementara yang membantu komunitas menemukan kembali kekuatannya, seperti tenaga profesional.
Kesimpulan
Dengan demikian, community-based social healing dapat dipahami sebagai proses penyembuhan yang menempatkan komunitas sebagai pusat, tanpa melupakan peran individu di dalamnya. Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam konteks trauma kolektif, di mana luka yang ditinggalkan bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial dan kultural. Indonesia sendiri tidak asing dengan peristiwa yang melahirkan trauma kolektif, mulai dari bencana alam, pandemi, hingga demonstrasi yang berujung pada kekerasan sosial. Situasi-situasi ini menunjukkan bahwa rasa aman, kebersamaan, dan solidaritas bisa goyah, namun juga dapat dibangun kembali melalui kekuatan komunitas.
Pada akhirnya, penyembuhan tidak berhenti pada individu, tetapi juga harus menyentuh lapisan sosial yang lebih luas. Ketika komunitas mampu memulihkan dirinya, ia tidak hanya menguatkan anggotanya, tetapi juga menciptakan fondasi bagi ketahanan sosial bangsa di masa depan. Dengan kata lain, menghadapi trauma kolektif di Indonesia memerlukan keberanian untuk pulih bersama. Hanya melalui kebersamaan, luka yang dialami dapat benar-benar diubah menjadi kekuatan.
Untuk dapat mengenali potensimu dengan baik, kalian dapat menemukan layanan asesmen psikologi terbaik hanya di biro psikologi resmi Assessment Indonesia, mitra terpercaya untuk kebutuhan psikotes.
References:
American Psychological Association. (2024). Collective trauma. Apa.org. https://www.apa.org/about/governance/president/grief-toolkit/collective-trauma.pdf
Fanahei, R. (2024). Community-Based social healing, community healing, and the role of “healing leader.” Grail of Science, 36, 501–510. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.16.02.2024.088